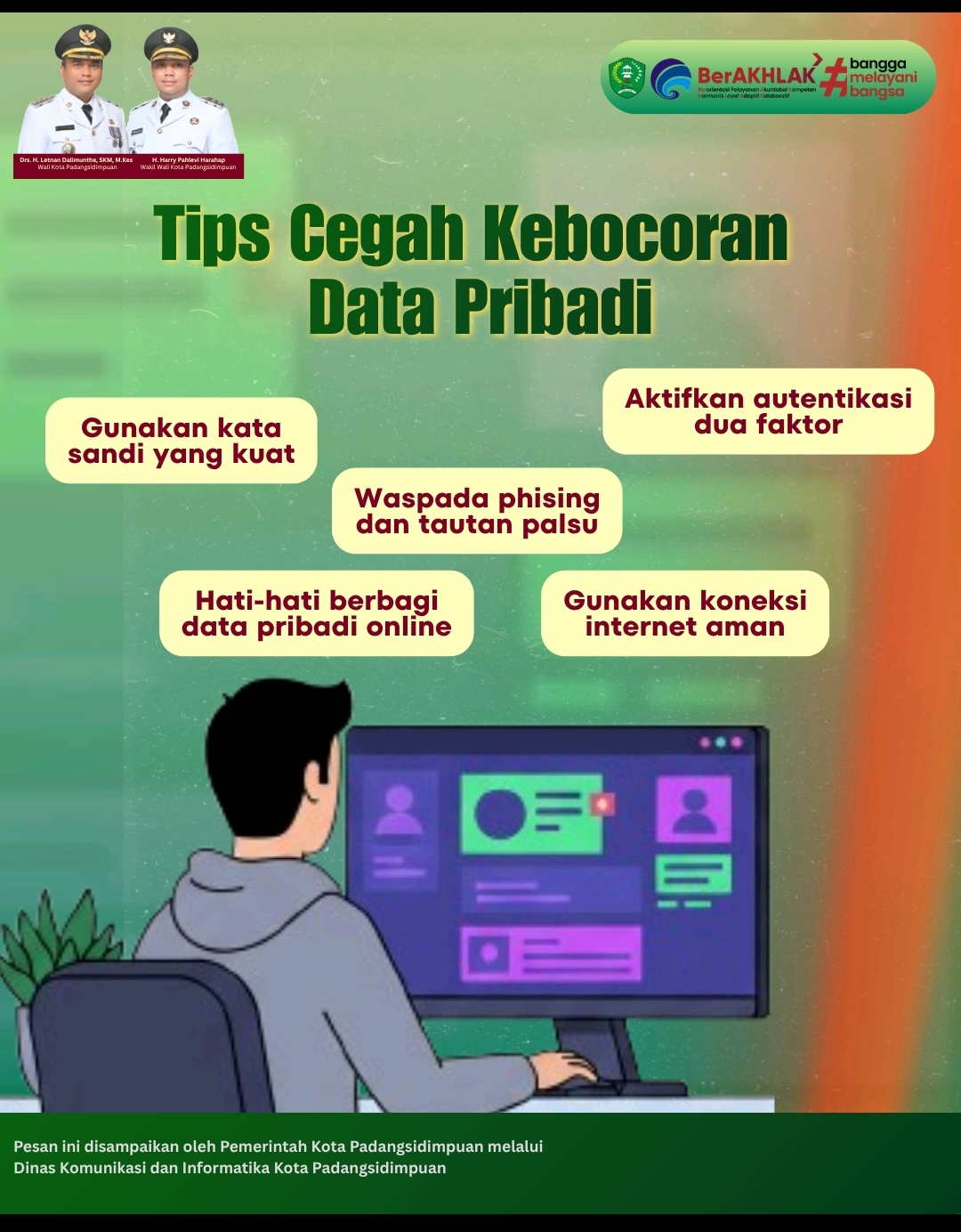Deru Mesin di Jembatan Tagilang Julu

Tahun 1980, udara di perbatasan Mandailing Natal (Kala itu masih Tapanuli Selatan) tidak pernah benar-benar bersih dari debu merah. Di telingaku, suara raungan mesin diesel bukan lagi kebisingan, melainkan musik harian yang menandakan kehidupan sedang berdenyut.
“Naiklah cepat! Tapi pegangan yang kuat, ya!” teriak seorang supir truk logging milik PT. Aek Gadis Timber.
Aku, seorang bocah dengan sandal jepit yang sudah tipis, memanjat kabin tinggi truk raksasa itu.
Di belakangku, tumpukan kayu balok berdiameter raksasa—hasil tebangan dari jantung hutan Mujur Timber Group—seolah siap menelan siapa saja yang lengah. Aku tidak takut. Bagiku, truk ini adalah kereta kencana yang akan membawaku bertemu pahlawanku: Ayah.
Perjalanan dari Pondok Rambe terasa lambat namun mendebarkan. Jalan perusahaan itu membelah hutan lebat, berkelok-kelok mendaki bukit. Setiap kali ban besar truk menghantam lubang, tubuhku terguncang hebat. Dari jendela, aku melihat deretan pohon meranti yang menjulang, menyembunyikan sinar matahari pagi.
“Mau jemput Bapak di Tagilang Julu?” tanya supir itu sambil mengunyah sirih. Aku mengangguk mantap.
Tagilang Julu adalah nama yang sakral bagiku. Di sana, di dekat jembatan kayu yang melintasi sungai berarus deras, Ayah sedang “mencari kehidupan”. Ayah adalah satu dari sekian banyak pria tangguh yang bertaruh nyawa di bawah naungan HPH, memastikan kayu-kayu terbaik sampai ke hilir demi sesuap nasi.
Setelah berjam-jam menembus kabut dan debu, sayup-sayup terdengar suara air terjun dan benturan kayu. Jembatan Tagilang Julu tampak di depan mata—sebuah konstruksi kayu yang gagah namun tampak rapuh di hadapan alam yang liar.
Truk berhenti dengan desisan rem angin yang panjang. Di kejauhan, aku melihat sesosok pria bertopi lusuh dengan baju yang basah oleh keringat dan minyak mesin. Ia sedang memeriksa rantai pengikat kayu. Begitu melihatku turun dari truk, wajahnya yang keras mendadak luluh.
Senyumnya merekah di balik noda tanah.
“Kenapa ke sini? Hutan ini bukan tempat main, Nak,” ucap Ayah sambil mengangkatku ke pundaknya. Aroma tubuhnya—campuran antara peluh, asap knalpot, dan getah kayu—adalah aroma paling menenangkan yang pernah kukenal.
Sore itu, di tepi Jembatan Tagilang Julu, kami duduk berdua. Ayah membagi sebungkus nasi kering dengan lauk seadanya. Rasanya pahit karena perjuangannya yang berat, namun terasa manis karena kasih sayangnya yang tak terbatas.
Tahun-tahun berlalu, PT. Aek Gadis Timber mungkin tinggal nama dalam catatan sejarah industri perkayuan, namun deru mesin dan kenangan di Tagilang Julu tetap menderu kencang dalam ingatanku. Di jembatan itulah aku belajar, bahwa kehidupan harus dicari, bahkan jika harus menembus hutan paling sunyi sekalipun.
Gema Sunyi di Lubuk Parira
Waktu ternyata adalah mesin penghancur yang paling sunyi. Puluhan tahun berlalu sejak terakhir kali aku berpijak di bak truk logging PT. Aek Gadis Timber. Hari ini, aku mencoba kembali ke arah Tagilang Julu, mencari sisa-sisa jejak kaki Ayah yang mungkin masih tertinggal di tanah merah itu.
Namun, alam telah mengambil kembali miliknya.
Jalan perusahaan yang dulunya lebar dan gagah, tempat mobil-mobil raksasa Mujur Timber menderu-deru, kini tak lebih dari setapak sempit yang ditelan belukar. Tak ada lagi suara klakson yang membelah rimba. Tak ada lagi debu merah yang beterbangan. Mobil tak lagi bisa lewat; besi dan ban karet telah kalah oleh akar pohon dan rotan yang merambat.
Aku berdiri di titik di mana Jembatan Tagilang Julu seharusnya berada. Namun, jembatan legendaris itu kini hanya tinggal kenangan. Tiang-tiangnya mungkin sudah hanyut dibawa banjir, atau melapuk menjadi tanah. Sungai di bawahnya tetap mengalir, namun ia tak lagi menyaksikan kepulauan kayu balok yang melintas di atasnya.
Ingatanku melayang jauh ke hulu, menuju Aek Raso, terus mendaki ke arah Lubuk Parira hingga Banua Sulang Aling. Di sana, dulu adalah medan tempur bagi para pencari kehidupan. Medan yang begitu berat, hingga orang-orang tua kita menciptakan pantun sebagai penghibur lara sekaligus pengingat akan kerasnya nasib.
Sambil menatap jalanan yang tertutup semak menuju Lubuk Parira, aku berbisik pelan, mengulangi rima yang dulu sering kudengar di sela-sela kepulan asap rokok para pekerja:
“Aek raso, manakkok tu lubuk parira…”
(Air Raso, mendaki ke Lubuk Parira…)
“On dope baru taraso, mandokkonna madung malla…”
(Ini baru terasa, mengatakannya pun sudah malu…)
Kalimat itu bergetar di dadaku. Pantun itu bukan sekadar rima tentang geografi, melainkan tentang harga diri. Tentang bagaimana rasa lelah yang menghujam tulang saat mendaki tanjakan Lubuk Parira tidak boleh dikeluhkan. Ada rasa malu jika harus mengaku kalah pada keadaan. Ayah dan kawan-kawannya dulu memendam lelah itu dalam-dalam, menyembunyikannya di balik senyum saat membawa pulang sedikit uang untuk kami di Pondok Rambe.
Kini, menuju Aek Raso hingga Banua Sulang Aling terasa seperti menuju dunia yang hilang. Hutan telah menutup rapat pintu masa lalu. Namun, bagiku yang berdiri di sini, Jembatan Tagilang Julu tetap berdiri kokoh di dalam kepala.
Meski jalannya sudah mati bagi roda kendaraan, jalan itu akan selalu hidup dalam setiap detak jantungku. Karena di situlah, di antara deru mesin yang kini sunyi, aku belajar bahwa “mencari kehidupan” adalah tentang keberanian untuk terus mendaki, meski lidah sudah kelu untuk sekadar mengaduh.
Cerpen oleh: Adnan Buyung Lubis (ABL)